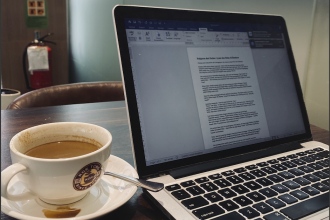Kalau nanti hujannya sudah reda, kita makan malam di luar lagi, ya. Seolah tak terjadi apa-apa. “Kalau nanti hujannya sudah reda, kita makan malam di luar lagi, ya.”
Begitu sederhana, begitu ringan, dan betapa indahnya hidup kalau semua masalah hanya menunggu cuaca membaik. Seolah yang tenggelam hanyalah kenangan, bukan rumah, bukan ladang, bukan nyawa.
Mungkin, setelah genangan air surut, kita bisa kembali menyeruput kopi sambil membahas betapa alam kini semakin tak bersahabat. Kita akan berkata dengan wajah prihatin namun tetap sambil menggenggam ponsel terbaru bahwa bencana ini sungguh memprihatinkan. Namun, tentu saja, kepedulian kita tak boleh berlebihan. Cukup satu unggahan story disertai hashtag #PrayForSiapaPunYangSedangDilandaBencana, lalu selesai. Dunia harus tahu bahwa kita sudah peduli. Setidaknya, peduli untuk dilihat.
Sementara itu, Aceh, Sumatera Utara, Sibolga, Padang, dan sekian wilayah lain yang sudah duluan menenggelamkan mimpinya mungkin akan tersenyum pahit melihat betapa hebatnya kita memberi simpati dari jarak aman jauh dari lumpur, jauh dari kedinginan, jauh dari bau pengungsian yang tak pernah masuk dalam estetika feed Instagram.
Kalau hujan sudah reda nanti, kita makan malam di luar lagi, ya.
Tenang saja, alam pasti memaafkan kita. Kan katanya alam itu baik? Sabar? Penuh cinta? Seperti ibu yang tidak pernah marah meski anak-anaknya membakar paru-parunya, mengikis kulitnya, menggali rahasianya, dan menebang setiap helai rambut hijaunya. Karena toh kalau banjir datang, kita tinggal menyalahkan hujan, bukan hulu sungai yang kita gusur, bukan bukit yang kita telanjangi, bukan keserakahan yang kita jadikan takdir.
Lihat betapa kreatifnya kita: kerusakan lingkungan bisa disulap menjadi teka-teki yang jawabannya selalu di luar diri kita.
Ada banjir?
Salah cuaca.
Ada longsor?
Salah kemiringan tanah.
Ada gempa?
Salah lempeng bumi.
Sungguh menyenangkan hidup sebagai spesies yang tak pernah salah. Kita selalu punya kambing hitam. Bahkan ketika kambing-kambing terakhir punah, kita mungkin akan menyalahkan kambing itu karena tidak cukup cepat beradaptasi.
Tapi jangan khawatir, kita masih bisa menormalisasi segalanya. Kita ahli. Kita bisa membangun rumah di bantaran sungai, lalu terkejut ketika sungai kembali menagih haknya. Kita bisa menanam bangunan beton di mana-mana, lalu frustrasi ketika air tak menemukan jalan pulang selain ke ruang tamu kita. Kita bisa menebang pohon tiap hari, lalu menangis histeris menanyakan di mana pelindung kita saat tanah mulai bergerak.
Namun percayalah, semua ini hanyalah sementara.
Hujan pasti akan reda. Dan setelah itu, kita bisa makan malam di luar lagi dengan bangga, dengan syukur, dengan napas lega, karena kita telah berhasil bertahan satu kali lagi tanpa belajar apa pun.
Ah, betapa luar biasanya manusia.
Makhluk yang menciptakan bencana, menyalahkan alam, lalu memohon keselamatan kepada langit yang sama yang ia kotori.
Yang tragis bukanlah ketika bumi marah.
Yang tragis adalah ketika manusia berpikir ia masih pantas dimarahi seolah kita pernah mendengarkan.
Sebab pada suatu hari nanti, hujan mungkin benar-benar akan reda.
Bukan karena alam memaafkan,
tetapi karena sudah tak ada lagi yang perlu dibersihkan.
Saat itu tiba, makan malam di luar tidak lagi mungkin.
Karena “luar” itu mungkin sudah hilang
.