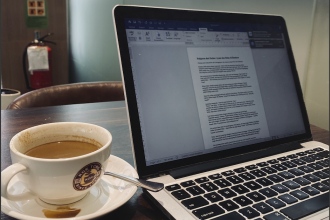November 2025.
Sudah delapan tahun sejak pertama kali saya menjejak Lombok, saat gempa besar mengguncang dan meninggalkan luka mendalam bagi banyak orang. Ketika itu saya masih mahasiswa S2 semester satu di Yogyakarta, baru mulai memahami dunia kemanusiaan bukan hanya dari teori, tapi dari kenyataan yang tak selalu mudah dihadapi.
Sebelum berangkat, saya menelpon ayah di Sumatera Utara.
“Pak, izinkan aku jadi relawan untuk gempa Lombok. Aku berangkat dalam keadaan selamat. Kalau nanti pulang tinggal jasad, tolong ikhlaskan, ya.”
Di seberang sana, ayah terdiam cukup lama sebelum menjawab pelan,
“Kalau itu yang kamu niatkan untuk kebaikan, pergilah. Tapi jaga diri baik-baik. Bapak tunggu kamu pulang.”
Itu percakapan yang tak pernah saya lupakan. Dari telepon itu, saya belajar bahwa setiap langkah kemanusiaan selalu dimulai dari doa dan keberanian yang lahir dari restu seseorang yang kita cintai.
Hari ini, saya kembali ke Lombok. Masih dengan wajah-wajah relawan yang dulu bersama-sama berada di tengah puing, hanya saja dalam suasana yang berbeda. Kini saya hadir sebagai narasumber dalam kegiatan “Bincang Baik”, berbagi pengalaman kepada relawan dari berbagai daerah di Indonesia.
Kegiatan ini terasa lebih dari sekadar diskusi. Ia seperti ruang refleksi yang mengingatkan saya akan perjalanan panjang: dari seorang relawan lapangan yang memanggul logistik dan membantu evakuasi, menjadi seseorang yang berbagi tentang makna kemanusiaan itu sendiri.
Di tengah sesi, salah satu peserta bertanya,
“Bagaimana caranya tetap konsisten dalam misi kemanusiaan, di tengah kesibukan dan rasa lelah yang kadang datang?”
Pertanyaan itu membuat saya terdiam. Karena sesungguhnya, mempertahankan semangat kemanusiaan di tengah kehidupan yang terus bergerak bukan hal mudah.
Ingatan saya kembali pada 2018, pada seorang anak laki-laki berusia sekitar tiga tahun yang saya temui di lokasi bencana. Tubuhnya berdebu, matanya kosong, dan di tangannya tergenggam sandal kecil. Ia kehilangan seluruh keluarganya. Saya duduk di sampingnya, tanpa kata. Hanya menggenggam tangannya. Dari anak kecil itu, saya belajar bahwa kemanusiaan tidak selalu berarti melakukan hal besar. Kadang, ia hanya tentang keberanian untuk hadir.
Delapan tahun berlalu, dan kini ayah sudah tiada. Beliau tak sempat tahu bahwa hari ini saya kembali ke Lombok, bukan untuk menolong, tapi untuk berbagi makna di balik semua pengalaman itu. Namun saya percaya, doa beliau tetap menyertai — sama seperti dulu, ketika langkah pertama saya di tanah ini diiringi restu yang sederhana namun kuat.
Konsistensi dalam kemanusiaan, bagi saya, bukan soal seberapa sering kita turun ke lapangan. Ia soal menjaga nurani agar tetap hidup, agar tetap peka, bahkan saat dunia di sekitar kita sibuk meninabobokan empati.
Hari ini saya tidak lagi membawa nasi bungkus atau logistik, tapi saya membawa cerita. Cerita tentang bagaimana luka mengajarkan empati, kehilangan menumbuhkan cinta, dan doa menguatkan langkah.
Mungkin itulah esensi menjadi relawan: bukan sekadar hadir di tengah bencana, tapi memastikan bahwa hati kita tidak ikut hancur, bahwa kita tetap mampu melihat manusia di balik setiap tragedi.
Pada akhirnya, misi kemanusiaan bukan tentang siapa yang paling kuat bertahan di lapangan, tetapi tentang siapa yang tetap membawa hati, bahkan setelah medan bencana berubah menjadi kenangan.