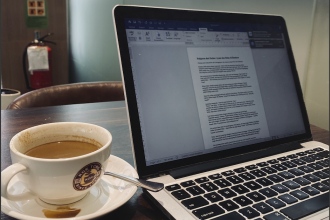Pertemanan sering dipahami hanya sebagai kebersamaan, padahal ia jauh lebih dari itu. Pertemanan adalah ruang belajar, tempat kita menyaksikan manusia tanpa topeng. Dari orang lain, kita menemukan pantulan tentang siapa kita sebenarnya. Dari cara mereka bersikap, kita belajar bagaimana seharusnya manusia hidup.
Teman Kupang adalah salah satu pantulan itu. Ia datang dari Timur, dari kota yang dikepung laut. Laut yang keras, berangin, dan penuh terik membentuk karakternya: tegas, jujur, dan tidak suka berbelit. Dari sana, ia membawa kejujuran yang kadang membuat orang lain kikuk, tapi justru meneguhkan wibawa. Ia lembut, tapi tidak rapuh. Ia tidak enakan, tapi tak bisa disepelekan. Ia kaya, tetapi tidak pernah menjadikan harta sebagai alat ukur dirinya. Namun, ia juga menyerap jiwa Jogja. Jogja mengajarkannya tanah yang teduh, kesabaran dalam langkah, dan kesederhanaan yang tidak pernah habis diajarkan. Jika Kupang memberinya keberanian laut, Jogja memberinya keseimbangan tanah. Dari laut ia belajar ketegasan, dari tanah ia belajar kerendahan hati. Dari pertemuan dua unsur itu lahirlah pribadi yang harmonis: sederhana namun kokoh, lembut namun berwibawa.
Namun hari ini kita semua sama-sama tahu bahwa pertemanan bukan lagi perkara sederhana. Dunia modern justru membuat banyak orang ragu pada kata “teman”. Ada terlalu banyak cerita tentang pengkhianatan. Teman yang menusuk dari belakang dalam bisnis; teman yang merebut pasangan dalam percintaan; teman yang memanfaatkan kepercayaan untuk kepentingan pribadi; bahkan teman yang meninggalkan begitu saja di saat kita jatuh. Setiap generasi punya ceritanya sendiri. Orang tua kita mengenang sahabat yang tiba-tiba jadi lawan dalam politik. Generasi kita sendiri sering menghadapi kawan kerja yang diam-diam menjegal demi promosi. Bahkan di generasi lebih muda, pengkhianatan bisa datang hanya karena komentar di media sosial yang salah tafsir.
Sejarah pun penuh dengan kasus seperti itu. Julius Caesar, pemimpin yang paling berkuasa di zamannya, runtuh bukan karena musuh, melainkan oleh tikaman sahabatnya sendiri, Brutus. Pengkhianatan itu menegaskan bahwa tidak ada kekuatan sebesar apa pun yang bisa bertahan jika dikhianati dari dalam lingkaran terdekat. Dalam dunia bisnis, banyak perusahaan besar runtuh karena orang dalam yang dianggap teman, justru mengkhianati kepercayaan dan meruntuhkan segalanya. Bahkan dalam lingkup kecil, berapa banyak kisah orang yang hidupnya hancur karena percaya penuh pada sahabat yang ternyata memperalat mereka?
Namun, justru di titik itu arti pertemanan yang sejati menemukan maknanya. Karena di tengah banyaknya pengkhianatan, kita menemukan figur-figur yang memilih setia. Lihatlah kisah Nelson Mandela. Dua puluh tujuh tahun ia dipenjara, namun ia tetap memiliki sahabat-sahabat yang setia mengirim kabar, menunggu, dan menjaga nama baiknya di luar. Mereka bukan hanya kawan, tetapi penopang kemanusiaan. Atau kisah Gus Dur, yang sepanjang hidupnya selalu dikelilingi oleh sahabat lintas agama, lintas golongan, yang bertahan mendampinginya meski dunia politik Indonesia begitu keras dan penuh intrik. Mereka menunjukkan bahwa kesetiaan dalam pertemanan masih mungkin, bahkan di dunia yang sering penuh pengkhianatan.
Di sisi lain, ada juga orang-orang sederhana yang memberi teladan besar. Seorang ibu di kamp pengungsian yang tetap berbagi roti terakhirnya kepada tetangga, karena ia tahu lapar tidak boleh ditanggung sendirian. Seorang nelayan yang menolong kapal lain di tengah badai, meski tahu risikonya bisa kehilangan perahu sendiri. Seorang tukang becak di Jogja yang rela menunggu temannya sakit seharian di rumah sakit, padahal hari itu ia tidak akan mendapat penghasilan. Mereka bukan tokoh besar, tidak tercatat dalam buku sejarah, tetapi dalam tindakan kecil itu, mereka menunjukkan makna sejati dari pertemanan: hadir tanpa syarat, setia tanpa pamrih, memberi tanpa hitungan.
Teman Kupang, dalam sikapnya yang lembut namun berintegritas, adalah representasi dari semua itu. Ia tidak menonjol dengan prestasi, tetapi juga tidak bisa disepelekan. Ia tidak menaklukkan dunia dengan kata-kata, tetapi meneguhkan dunia dengan kehadiran yang tenang. Ia mengingatkan kita bahwa persahabatan sejati bukan tentang siapa yang paling sering ada di samping kita, melainkan siapa yang membuat kita tetap berani menjadi diri sendiri. Ia juga mengajarkan tentang emosi. Bahwa manusia tidak harus meluap-luap untuk bisa dimengerti. Ada kekuatan dalam kesederhanaan sikap: tatapan jujur, genggaman singkat, atau diam yang penuh arti. Dan ketika saatnya perpisahan tiba, ia menunjukkan bahwa berpisah tidak selalu berarti kehilangan. Ada perpisahan yang justru mengajarkan kita untuk membawa nilai orang lain ke dalam hidup kita sendiri.
Semua itu sebenarnya sudah terangkum dalam namanya sendiri. Wira berarti ksatria, pahlawan, seorang yang berani berdiri tegak dengan keberanian hati. Hardinata bermakna kemuliaan dan keagungan, bukan dari jabatan atau harta, melainkan dari akhlak dan konsistensi. Aji berarti nilai, sesuatu yang berharga, harga diri yang tak bisa diperdagangkan. Ia adalah anak seorang perwira. Dari darah itu ia mewarisi disiplin dan ketegasan. Namun, ia memilih bentuk keberanian yang berbeda: bukan keberanian menaklukkan orang lain, melainkan keberanian untuk tetap jujur, tetap sederhana, dan tetap manusiawi.
Kupang memberinya laut, Jogja memberinya tanah. Dari pertemanan dengannya, kita belajar bahwa hidup bukanlah tentang mengejar sorot lampu, melainkan tentang menjaga diri tetap utuh di tengah perubahan. Ia adalah pengingat bahwa manusia bisa menjadi berharga bukan karena tinggi pangkatnya, bukan karena banyak prestasinya, melainkan karena ia tidak pernah kehilangan integritasnya.
Dan semua itu ada pada satu nama: Wira.