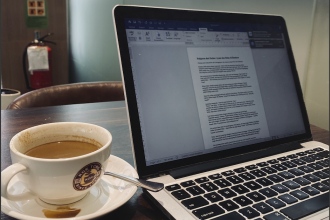Sumber Gambar : https://biografieonline.it/biografia-hermann-hesse
Kita hidup di dunia yang nyaris tidak pernah diam. Pagi dimulai dengan notifikasi, malam ditutup dengan scroll tak berujung. Otak kita terus dijejali oleh kabar, opini, perdebatan, dan tuntutan menjadi “versi terbaik dari diri kita” secepat mungkin. Tapi di antara semua kebisingan ini, siapa yang mengajarkan kita untuk berhenti sejenak?
Herman Hesse, penulis asal Jerman yang mungkin jarang muncul di linimasa, justru menyimpan pelajaran berharga bagi zaman kita. Ia menulis bukan untuk menggurui, tapi untuk mengajak pembacanya berjalan pelan-pelan ke dalam diri. Lewat tokoh-tokoh seperti Siddhartha, Emil Sinclair, atau Harry Haller, Hesse berbicara tentang sesuatu yang kini langka: kesunyian yang menyembuhkan.
Di era yang dipenuhi dengan dering notifikasi, arus informasi yang tiada henti, dan kelelahan mental akibat layar yang terus menyala, keheningan menjadi barang langka. Kita hidup di zaman ketika pikiran nyaris tak pernah diam. Bahkan saat tubuh beristirahat, otak kita terus diganggu oleh algoritma yang memanggil-manggil perhatian. Di tengah kebisingan inilah, karya-karya Herman Hesse terasa seperti oase tempat kita diajak untuk kembali diam, menepi, dan bertanya: apa sebenarnya yang kita cari dalam hidup ini?
Hesse, melalui novel-novelnya seperti Siddhartha dan Demian, tidak sekadar menulis cerita. Ia menawarkan perjalanan batin yang penuh kontemplasi, refleksi, dan pertarungan antara diri sejati dengan dunia luar yang menyesatkan. Siddhartha, misalnya, adalah kisah pencarian spiritual yang tidak didorong oleh dogma atau ambisi, tetapi oleh kerinduan mendalam akan keutuhan diri. Dalam dunia digital yang mendorong kita untuk selalu menjadi versi “terbaik”, “terupdate”, dan “terlihat produktif”, pesan Hesse tentang keheningan terasa membebaskan.
Sunyi, bagi Hesse, bukan pelarian. Ia adalah jalan pulang. Dalam Siddhartha, sang tokoh justru menemukan kebijaksanaan bukan di tengah keramaian wacana, tetapi di tepian sungai tempat ia belajar mendengarkan aliran hidup, bukan membanjirinya. Kita, hari ini, mungkin tak punya sungai itu. Tapi kita punya jeda. Kita punya momen hening, jika berani menciptakannya. Kita hanya perlu menonaktifkan notifikasi.
Burnout, yang kini menjadi epidemi baru di kalangan profesional dan generasi muda, bukan hanya karena terlalu banyak bekerja. Sering kali, ia lahir dari kehilangan makna. Kita terlalu sibuk mengejar, sehingga lupa bertanya: untuk apa semua ini? Di sinilah Demian berbicara. Tokohnya, Emil Sinclair, bergulat dengan dua dunia: dunia terang yang penuh aturan dan dunia gelap yang penuh misteri batin. Pertarungan itu merepresentasikan kegelisahan banyak orang hari ini yang merasa hidupnya dikendalikan oleh ekspektasi eksternal likes, views, konten viral namun merasa hampa di dalam.
Melalui Hesse, kita diajak untuk berani berjalan ke dalam. Bukan dengan bising, tapi dengan sunyi. Bukan dengan kompetisi, tapi dengan kontemplasi. Inilah esensi dari apa yang kini dikenal sebagai digital minimalism gerakan untuk menggunakan teknologi secara sadar, bukan impulsif. Tidak semua yang bisa dilihat harus dilihat. Tidak semua yang bisa dikomentari harus dikomentari.
Mungkin sudah saatnya kita menata ulang relasi dengan dunia digital. Bukan dengan membenci atau menjauhi sepenuhnya, tetapi dengan memberi ruang bagi kesunyian untuk hadir. Membaca satu halaman Hesse dalam diam, bisa menjadi awal yang sederhana namun bermakna.
“Kebijaksanaan tidak dapat diwariskan. Kebijaksanaan yang benar harus ditemukan sendiri, melalui perjalanan batin.”- Siddhartha, Herman Hesse
Kita tidak bisa mengubah dunia yang terus bergerak cepat. Tapi kita bisa mengubah cara kita berjalan di dalamnya. Kadang, yang kita butuhkan bukan lebih banyak informasi, tapi lebih banyak keheningan untuk mencerna apa yang sebenarnya penting.
Salah satu keistimewaan Herman Hesse adalah keberaniannya menulis tentang patah hati eksistensial. Ia tidak memberikan solusi instan atau motivasi klise, tetapi mengajak pembaca untuk mengakui rasa sakit, kebingungan, bahkan kekosongan hidup sebagai bagian sah dari perjalanan manusia. Dalam Steppenwolf, Hesse menggambarkan tokoh Harry Haller sebagai sosok yang terbelah: satu sisi ingin hidup seperti manusia biasa, sisi lain ingin bebas seperti serigala liar. Kita yang hidup di era serba-performatif ini pun sering merasakan dilema yang sama antara menjadi diri sendiri atau menjadi seperti yang diharapkan.
Dalam banyak karyanya, Hesse menunjukkan bahwa keraguan adalah awal dari kebijaksanaan. Ia menolak gagasan bahwa hidup harus selalu penuh kepastian. Justru dalam ketidakpastianlah manusia belajar untuk mengenali dirinya. “Kebenaran tidak bisa diajarkan,” tulisnya dalam Siddhartha, “Ia hanya bisa dialami.” Maka, alih-alih mencari jawaban di luar, Hesse mengajak kita untuk duduk bersama pertanyaan-pertanyaan kita sendiri. Ia memuliakan proses, bukan hasil. Dalam dunia hari ini yang terobsesi dengan resolusi cepat dan produktivitas, ajakan Hesse untuk berdiam dan merenung terasa seperti undangan pulang ke hakikat kemanusiaan.
Hal lain yang menarik dari Hesse adalah bagaimana ia melihat kesendirian sebagai ruang tumbuh, bukan kutukan. Tokoh-tokoh dalam novelnya sering digambarkan berjalan sendiri, menjauh dari keramaian, bukan karena anti-sosial, tetapi karena mereka sedang belajar mengenal siapa diri mereka di luar identitas sosial. Dalam konteks hari ini, kesendirian bisa menjadi bentuk perlawanan terhadap kultur fear of missing out (FOMO) yang membuat banyak orang merasa selalu tertinggal jika tidak terus hadir secara online. Dari Hesse, kita belajar bahwa missing out kadang justru memberi ruang untuk finding in.
Hesse juga mengajarkan bahwa hidup bukan soal menjadi sempurna, tetapi menjadi utuh. Dalam surat-surat pribadinya, ia sering menulis tentang kegagalan, depresi, bahkan keinginannya untuk mundur dari dunia. Tapi justru dari kegagalan itulah lahir karya-karya yang kuat dan jujur. Ini adalah pesan yang kuat bagi siapa pun yang sedang merasa “tidak cukup” dalam hidupnya. Di balik krisis, ada potensi transformasi.
Membaca Hesse bukan seperti membaca manual hidup. Ia seperti cermin yang tidak memberi tahu harus ke mana, tetapi menampilkan apa adanya siapa diri kita hari ini. Dan kadang, itu lebih dari cukup. Dalam dunia yang terus menuntut kita untuk maju dan cepat, Hesse mengajarkan: perlambatlah, dengarkan sunyi, dan jangan takut berjalan sendiri. Karena siapa tahu, justru di kesendirian itulah suara hati terdengar paling jernih.